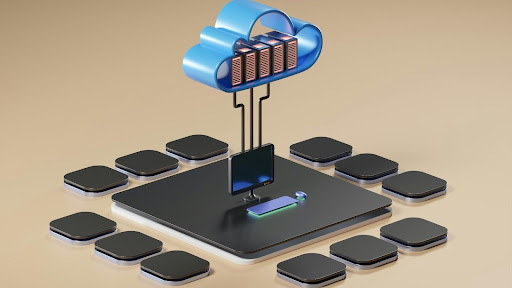Halo, developer! Pasti kamu sudah nggak asing lagi dong sama istilah microservices? Arsitektur ini memang lagi naik daun dan banyak banget dipakai perusahaan-perusahaan besar sekelas Netflix atau Gojek. Janjinya sih bikin pengembangan jadi lebih cepat, aplikasi jadi lebih skalabel, dan tim jadi lebih mandiri. Tapi, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan arsitektur ini. Ada banyak banget sisi lain yang seringkali terlewat atau baru disadari pas proyek sudah jalan. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas nih sisi lain dari microservices, yaitu kekurangan Microservices. Kapan sih sebenarnya dia nggak tepat guna buat proyek kita? Yuk, kita bahas bareng-bareng di api.co.id.
Sebelum kita terlalu jauh menyelami berbagai tantangan ini, ada baiknya kita sedikit menyegarkan ingatan tentang apa itu arsitektur microservices. Secara garis besar, microservices itu sebuah pendekatan di mana aplikasi besar dipecah jadi layanan-layanan kecil yang independen, masing-masing punya fungsi spesifik dan bisa dikembangkan, di-deploy, bahkan di-scale secara terpisah. Kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi tentang konsep dasarnya, termasuk pengertian, karakteristik, dan cara kerjanya, kamu bisa mampir ke artikel kami yang membahas secara lengkap apa itu arsitektur microservice.
Memang sih, saya akui, microservices itu punya banyak banget daya tarik. Kemampuan untuk menskalakan bagian-bagian tertentu dari aplikasi tanpa harus mengubah keseluruhan sistem, fleksibilitas teknologi yang memungkinkan tiap layanan pakai bahasa atau framework terbaik, sampai peningkatan ketahanan sistem kalau ada satu layanan yang gagal, itu semua adalah keunggulan yang sulit diabaikan. Bahkan, untuk perusahaan yang butuh pengembangan cepat dan update tren, microservices jadi pilihan yang tepat. Kalau kamu pengen tahu lebih jauh soal sisi positifnya, kami juga sudah pernah bahas lho tentang keunggulan arsitektur microservice. Tapi, di balik gemerlap kelebihannya itu, ada beberapa “ongkos” yang harus kita bayar, dan ini sering jadi alasan kenapa kekurangan Microservices bisa jadi mimpi buruk.

Kompleksitas yang Meningkat Secara Eksponensial
Salah satu kekurangan Microservices yang paling sering dikeluhkan adalah peningkatan kompleksitas. Kalau di monolit, semua ada di satu tempat, jadi kita nggak terlalu pusing mikirin komunikasi antar komponen. Nah, di microservices, setiap layanan itu kan independen. Ini berarti ada banyak banget “bagian bergerak” yang harus diatur. Mulai dari service discovery, API Gateway, load balancing, sampai mekanisme komunikasi antar layanan (REST, gRPC, message queues) itu jadi hal-hal yang wajib dipikirkan matang-matang.
Bayangin deh, kalau kamu punya puluhan bahkan ratusan layanan, gimana cara layanan A tahu keberadaan layanan B? Gimana caranya mereka bisa ngobrol satu sama lain tanpa bikin leher gatal karena latency jaringan? Ini semua butuh infrastruktur tambahan yang nggak sederhana. Kita butuh tools orkestrasi seperti Kubernetes, yang meskipun powerful, juga menambah kurva pembelajaran dan biaya operasional. Lalu, kalau ada masalah, melacak alur permintaan dari satu layanan ke layanan lain itu bisa bikin pusing tujuh keliling. Ini bukan cuma soal kode, tapi juga tentang gimana tim berinteraksi dan menyelaraskan berbagai aturan serta prioritas mereka.
Mengelola Ketergantungan dan Komunikasi Antar Layanan
Di arsitektur microservices, satu permintaan pengguna bisa jadi melewati belasan layanan yang berbeda. Ketergantungan antar layanan ini jadi rumit banget. Misalnya, kalau layanan A butuh data dari layanan B, dan layanan B butuh data dari layanan C, terus layanan C lagi bermasalah, efeknya bisa menjalar ke mana-mana (cascading failures). Meskipun ide dasarnya adalah kegagalan satu layanan nggak mempengaruhi yang lain, tapi kenyataannya seringkali berbeda kalau kita nggak merancangnya dengan sangat hati-hati. Ini bisa bikin alert berhamburan dan bikin tim on-call terbangun di tengah malam tanpa bisa langsung tahu akar masalahnya ada di mana.
Belum lagi soal latensi jaringan. Di monolit, panggilan fungsi itu super cepat karena terjadi di dalam satu proses. Kalau di microservices, panggilan itu jadi permintaan jaringan yang jelas lebih lambat dan punya potensi kegagalan lebih tinggi. Jadi, kompleksitas bukan cuma di desain sistemnya, tapi juga di infrastruktur yang harus menopang komunikasi antar layanan ini.
related article: Strategi Migrasi Monolith ke Microservice yang Efektif
Overhead Operasional yang Lebih Tinggi
Salah satu janji microservices adalah bikin deployment lebih cepat dan mandiri. Tapi, di sisi lain, ini juga berarti kita punya lebih banyak hal yang harus di-deploy, di-manage, dan di-monitor. Tiap layanan butuh pipeline CI/CD-nya sendiri, butuh konfigurasi lingkungan yang terpisah, dan butuh sumber daya komputasi yang mungkin lebih banyak secara agregat. Ini yang sering disebut sebagai overhead Microservices atau operational overhead.
Misalnya, satu aplikasi monolitik mungkin bisa jalan di beberapa server. Tapi, kalau dipecah jadi 20 layanan microservices, kita bisa berakhir dengan 40-60 proses yang berjalan (termasuk replika untuk ketahanan). Ini belum termasuk load balancer dan messaging layers yang jadi penghubung antar layanan. Semakin banyak komponen, semakin banyak juga yang harus diurus. Ini bisa bikin biaya infrastruktur dan tim operasional jadi membengkak. Kita butuh tim SRE (Site Reliability Engineer) yang lebih spesialis dan lebih banyak, yang gajinya bisa 20-40% lebih tinggi dari peran operasional tradisional.
Peningkatan Biaya Infrastruktur
Jangan salah sangka, pindah ke microservices itu bukan berarti otomatis hemat biaya. Malah sebaliknya, seringkali ada biaya Microservices tersembunyi yang bikin kantong bolong. Kita butuh lebih banyak resource komputasi untuk tiap layanan dan sidecar (kalau pakai service mesh seperti Istio), biaya jaringan untuk komunikasi antar layanan, penyimpanan untuk log dan trace terdistribusi, dan biaya platform orkestrasi seperti Kubernetes.
Studi kasus menunjukkan bahwa untuk 100 layanan dengan sidecar Istio, biaya overhead sidecar saja bisa mencapai lebih dari $40.000 per tahun, itu pun belum termasuk biaya workload aplikasi utama. Jadi, meskipun microservices bisa membantu kita mengoptimalkan sumber daya di bagian tertentu, secara keseluruhan, total biaya kepemilikan (TCO) bisa jadi lebih tinggi karena peningkatan kompleksitas operasional dan infrastruktur yang diperlukan.
related article: Apa Itu Arsitektur Microservices: Revolusi Cara Kita Membangun Aplikasi Modern
Tantangan dalam Pengembangan dan Pengujian
Pengembangan di lingkungan microservices itu unik. Kalau di monolit, semua kode ada di satu repo, jadi gampang buat nyari atau nge-debug. Nah, di microservices, kita punya banyak repo yang tersebar, dan ngembangin fitur yang melibatkan beberapa layanan itu bisa jadi lebih rumit. Kita harus memastikan semua layanan bisa ngobrol dengan benar, apalagi kalau pakai teknologi yang berbeda-beda.
Yang nggak kalah pusing adalah soal pengujian atau testing Microservices. Bayangin, gimana caranya kita nguji sebuah fitur yang melibatkan 5-10 layanan yang berbeda? Uji unit per layanan masih bisa, tapi pas masuk ke uji integrasi, ceritanya jadi beda. Kita butuh lingkungan yang bisa mereplikasi kondisi produksi atau setidaknya lingkungan staging yang lengkap, dan ini sering jadi bottleneck. Membuat lingkungan pengembangan lokal yang bisa jalanin semua dependensi layanan itu hampir mustahil. Mocking atau simulating dependencies jadi penting, tapi ini juga butuh investasi tooling yang nggak sedikit.
Banyak tim developer yang bilang kalau testing microservices itu jadi tantangan besar. Kompleksitas interaksi antar layanan, banyaknya ketergantungan, dan skala sistem yang besar bikin strategi testing tradisional nggak lagi efektif. Uji end-to-end yang melibatkan banyak layanan jadi krusial, tapi juga jadi yang paling sulit dan memakan waktu.
related article: Ketahui Kelebihan Arsitektur Microservice Dibanding Monolith!
Manajemen Data Terdistribusi yang Rumit
Di microservices, idealnya setiap layanan punya database-nya sendiri (database per service). Tujuannya sih supaya layanan jadi independen dan nggak saling tergantung soal skema data. Tapi, ini juga berarti kita harus berurusan dengan data terdistribusi Microservices yang punya tantangan tersendiri, terutama soal konsistensi data dan transaksi terdistribusi.
Misalnya, ada transaksi yang melibatkan beberapa layanan, kayak proses order di e-commerce yang melibatkan layanan produk, layanan pembayaran, dan layanan inventaris. Kalau salah satu gagal, gimana caranya biar semua kembali ke kondisi semula (rollback) atau tetap konsisten? Kita nggak bisa lagi pakai transaksi database tradisional yang sifatnya ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) secara langsung di seluruh sistem. Kita harus pakai pola desain yang lebih kompleks, kayak Saga Pattern atau Two-Phase Commit, yang juga punya kompleksitas dan tantangan implementasinya sendiri.
Mengelola evolusi skema data di banyak database yang berbeda juga bukan perkara mudah. Perubahan di satu layanan bisa jadi butuh koordinasi dengan layanan lain yang menggunakan data tersebut. Ini butuh komunikasi yang sangat baik antar tim dan strategi migrasi data yang matang.
Kesulitan dalam Debugging dan Monitoring
Debugging Microservices itu ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kalau di monolit, cukup lihat satu log file atau satu proses untuk tahu akar masalahnya. Di microservices? Request dari user bisa lewat puluhan layanan. Jadi, kalau ada error, gimana caranya kita tahu layanan mana yang salah, atau di mana letak masalahnya? Kita butuh distributed tracing, log aggregation, dan monitoring tools yang canggih untuk bisa melihat alur permintaan secara menyeluruh.
Ini semua menambah kompleksitas operasional dan butuh investasi di tooling yang nggak murah. Alat-alat monitoring seperti Prometheus, Grafana, atau ELK Stack memang sangat membantu, tapi implementasi dan pengelolaannya juga butuh keahlian khusus dan sumber daya yang nggak sedikit. Tanpa tooling internal yang memadai, developer bisa menghabiskan banyak waktu cuma untuk mengecek health endpoint, me-restart service, atau melacak error di berbagai sistem.
Kapan Microservices Tidak Tepat Guna?
Melihat berbagai kekurangan Microservices di atas, penting banget buat kita tahu kapan sih sebenarnya arsitektur ini nggak tepat guna. Saya pribadi sering bilang, microservices itu bukan solusi universal yang cocok untuk semua masalah. Ada beberapa skenario di mana monolit justru bisa jadi pilihan yang lebih baik, atau setidaknya lebih aman untuk memulai:
- Proyek Skala Kecil atau MVP (Minimum Viable Product): Kalau proyek kamu masih kecil, timnya sedikit (kurang dari 10 developer), atau domain bisnisnya belum terlalu jelas, memulai dengan microservices itu ibarat menembak kaki sendiri. Kompleksitas di awal akan sangat membebani dan memperlambat pengembangan. Lebih baik mulai dengan monolit yang modular, lalu kalau memang perlu, baru dipecah nanti.
- Tim dengan Pengalaman Terbatas: Implementasi microservices butuh tim yang punya skill set tinggi di berbagai area, mulai dari distributed systems, container orchestration (Kubernetes), service mesh, sampai observabilitas tingkat lanjut. Kalau tim kamu belum siap, justru bisa jadi bumerang.
- Domain Bisnis yang Belum Stabil: Kalau kebutuhan bisnisnya masih sering berubah drastis, atau kamu belum punya pemahaman yang kuat tentang batasan-batasan domain, memecah aplikasi jadi layanan-layanan kecil itu bisa jadi kesalahan besar. Kamu bisa berakhir dengan distributed monolith, di mana layanan-layanan itu saling tergantung erat dan sulit diubah.
- Batas Waktu dan Anggaran yang Ketat: Mengimplementasikan microservices butuh investasi waktu dan uang yang besar di awal, baik untuk infrastruktur, tooling, maupun pelatihan tim. Kalau punya batasan yang sangat ketat, lebih baik fokus pada pengembangan fitur dengan arsitektur yang lebih sederhana dulu.
- Tidak Ada Kebutuhan Skalabilitas Independen yang Jelas: Kalau kamu tidak punya kebutuhan untuk menskalakan bagian-bagian tertentu dari aplikasi secara drastis dan terpisah, manfaat skalabilitas microservices jadi kurang relevan. Monolit yang di-scale secara vertikal atau horizontal pun bisa cukup untuk banyak kasus.
Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa arsitektur itu ibarat sebuah alat. Nggak ada alat yang sempurna untuk semua pekerjaan. Kekurangan Microservices itu nyata dan bisa sangat mahal harganya kalau kita salah pilih atau salah implementasi. Saya selalu percaya, lebih baik memulai dengan solusi yang sederhana, bekerja dengan baik, lalu evolusikan arsitektur sesuai dengan kebutuhan yang muncul seiring pertumbuhan proyek dan tim. Jangan sampai kita terjebak mengikuti tren tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dan tantangannya. Jadi, kapan dia tak tepat guna? Jawabannya ada di pemahaman mendalammu tentang proyek, tim, dan konteks bisnis yang kamu hadapi.